ins
Pekan depan Pameran Kegemilangan Sains dalam Tamadun Islam yang digelar di ibukota negara jiran Kuala Lumpur akan berakhir. Seperti diberitakan harian ini (10/01/07), pameran yang diselenggarakan oleh Kementerian Sains, Teknologi, dan Inovasi bekerjasama dengan Institute for the History of Arabic-Islamic Science Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt itu bertujuan membangkitkan kembali semangat dan kesadaran generasi muda akan pentingnya mempelajari dan menguasai sains dan teknologi. Lebih dari seratus artifak dan manuskrip dalam pelbagai bidang (kedokteran, astronomi, kartografi, teknik dan arsitektur) yang ditampilkan cukup membuat pengunjung berdecak kagum sekaligus bertanya-tanya: Bagaimana umat Islam berhasil mencapai kejayaan itu dan –yang lebih mengherankan lagi- mengapa semua itu kemudian lenyap?
Pekan depan Pameran Kegemilangan Sains dalam Tamadun Islam yang digelar di ibukota negara jiran Kuala Lumpur akan berakhir. Seperti diberitakan harian ini (10/01/07), pameran yang diselenggarakan oleh Kementerian Sains, Teknologi, dan Inovasi bekerjasama dengan Institute for the History of Arabic-Islamic Science Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt itu bertujuan membangkitkan kembali semangat dan kesadaran generasi muda akan pentingnya mempelajari dan menguasai sains dan teknologi. Lebih dari seratus
Kemajuan Sains dalam Sejarah Islam
Kemajuan Sains dalam Sejarah Islam
Awal kemunculan dan perkembangan sains di dunia Islam tidak dapat dipisahkan dari sejarah ekspansi Islam itu sendiri. Dalam tempo lebih kurang 25 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad saw (632 M), kaum Muslim telah berhasil menaklukkan seluruh jazirah Arabia dari selatan hingga utara. Ekspansi dakwah yang diistilahkan ‘pembukaan negeri-negeri’ (futuh al-buldan) itu berlangsung pesat tak terbendung. Bagai diterpa gelombang tsunami, satu persatu, kerajaan demi kerajaan dan kota demi kota berhasil ditaklukkan. Maka tak sampai satu abad, pada 750 M, wilayah Islam telah meliputi hampir seluruh luas jajahan Alexander the Great di Asia (Kaukasus) dan Afrika Utara (Libya, Tunisia, Aljazair, dan Marokko), mencakup Mesopotamia (Iraq), Syria, Palestina, Persia (Iran), Mesir, plus semenanjung Iberia (Spanyol dan Portugis) dan India.
Pelebaran sayap dakwah Islam ini tentu bukan tanpa konsekuensi. Seiring dengan terjadinya konversi massal dari agama asal atau kepercayaan lokal kedalam Islam, terjadi pula penyerapan terhadap tradisi budaya dan peradaban setempat. Proses interaksi yang berlangsung alami namun intensif ini tidak lain dan tidak bukan adalah gerakan “islamisasi” (ada juga yang lebih suka menyebutnya sebagai naturalisasi, integralisasi, atau assimilasi), dimana unsur-unsur dan nilai-nilai masyarakat lokal ditampung, ditampih dan disaring dulu sebelum kemudian diserap. Hal-hal yang positif dan sejalan dengan Islam dipertahankan, dilestarikan dan dikembangkan, sementara elemen-elemen yang tidak sesuai dengan kerangka dasar ajaran Islam ditolak dan dibuang.
Dalam proses interaksi tersebut, kaum Muslim pun terdorong untuk mempelajari dan memahami tradisi intelektual negeri-negeri yang ditaklukkannya. Ini dimulai dengan penerjemahan karya-karya ilmiah dari bahasa Yunani (Greek) dan Suryani (Syriac) ke dalam bahasa Arab pada zaman pemerintahan Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, Syria. Pelaksananya adalah para cendekiawan dan paderi yang juga dipercaya sebagai pegawai pemerintahan. Akselerasi terjadi setelah tahun 750 M, menyusul berdirinya Daulat Abbasiyyah yang berpusat di Baghdad. Khalifah al-Ma’mūn (w. 833 M) mendirikan sebuah pusat kajian dan perpustakaan yang dinamakan Bayt al-Hikmah. Menjelang akhir abad ke-9 Masehi, hampir seluruh korpus saintifik Yunani telah berhasil diterjemahkan, meliputi berbagai bidang ilmu pengetahuan, dari kedokteran, matematika, astronomi, fisika, hingga filsafat, astrologi dan alchemy. Muncullah orang-orang seperti Abu Bakr al-Razi (Rhazes), Jabir ibn Hayyan (Geber), al-Khawarizmi (Algorithm), Ibn Sina (Avicenna) dan masih banyak sederetan nama besar lainnya.
Kegemilangan itu berlangsung sekitar lima abad lamanya, ditandai dengan produktifitas yang tinggi dan orisinalitas luar biasa. Sebagai ilustrasi, al-Battani (w. 929) mengoreksi dan memperbaiki sistem astronomi Ptolemy, mengamati mengkaji pergerakan matahari dan bulan, membuat kalkulasi baru, mendesain katalog bintang, merancang pembuatan pelbagai instrumen observasi, termasuk desain jam matahari (sundial) dan alat ukur mural quadrant. Seperti buku-buku lainnya, karya al-Battani pun diterjemahkan ke bahasa Latin, yaitu De scientia stellarum, yang dipakai sebagai salah satu bahan rujukan oleh Kepler dan Copernicus. Kritik terhadap teori-teori Ptolemy juga telah dilontarkan oleh Ibn Rusyd (w. 1198) dan al-Bitruji (w. 1190). Dalam bidang fisika, Ibn Bajjah (w. 1138) mengantisipasi Galileo dengan kritiknya terhadap teori Aristoteles tentang daya gerak dan kecepatan. Demikian pula dalam bidang-bidang lainnya. Bahkan dalam hal teknologi, pada sekitar tahun 800an M di Andalusia (Spanyol), Ibn Firnas telah merancang pembuatan alat untuk terbang mirip dengan rekayasa yang dibuat Roger Bacon (w. 1292) dan belakangan dipopulerkan oleh Leonardo da Vinci (w. 1519).
Faktor Pemicu Kejayaan Sains
Melihat prestasi gemilang itu, wajarlah jika kemudian muncul pertanyaan bagaimana semua itu dapat terjadi? Jika dikaji dan ditelusuri dengan teliti, faktor-faktor yang telah memungkinkan dan mendorong kemajuan sains di dunia Islam pada saat itu ada lima. Pertama, berkat kesungguhan dalam mengimani mempraktekkan ajaran Islam sebagaimana tertuang dalam al-Qur’an dan Sunnah itu lahirlah individu-individu unggul yang pada gilirannya membentuk masyarakat madani Islami. Kedua, adanya motivasi agama. Seperti kita ketahui, kitab suci al-Qur’an banyak berisi anjuran untuk menuntut ilmu, membaca (iqra’), melakukan observasi, esplorasi, ekspedisi (siru fil ardhi), dan berfikir ilmiah rasional.
Al-Qur’an juga mengecam keras sikap dogmatis atau taklid buta. Begitu gencarnya ayat-ayat itu didengungkan, sehingga belajar atau mencari ilmu pengetahuan diyakini sebagai kewajiban atas setiap individu Muslim, dengan implikasi berdosalah mereka yang tidak melakukannya. Pada dataran praktis, doktrin ini membawa dampak sangat positif. Ia mendorong dan mempercepat terciptanya masyarakat ilmu (knowledge society) dan budaya ilmu (knowledge culture), dua pilar utama setiap peradaban.
Ketiga adalah faktor sosial politik. Tumbuh dan berkembangnya budaya ilmu dan tradisi ilmiah pada masa itu dimungkinkan antara lain ―jika bukan terutama― oleh kondisi masyarakat Islam yang, meskipun terdiri dari bermacam-macam etnis (Arab, Parsi, Koptik, Berber, Turki, dan lain lain), dengan latarbelakang bahasa dan budaya masing-masing, namun berhasil diikat oleh tali persaudaraan Islam. Dengan demikian terwujudlah stabilitas, keamanan dan persatuan. Para pencari ilmu maupun cendekiawan dengan leluasa dan aman bepergian ke pusat-pusat pendidikan dan keilmuan, dari Seville ke Baghdad, dari Samarkand ke Madinah, dari Isfahan ke Kairo, atau dari Yaman ke Damaskus. Ini belum termasuk mereka yang menjelajahi seluruh pelosok dunia Islam semisal Ibn Jubayr (w. 1217) dan Ibn Batūtah (w. 1377).
Ketiga adalah faktor ekonomi. Kesejahteraan masyarakat masa itu membuka kesempatan bagi setiap orang untuk mengembangkan diri dan mencapai apa yang diinginkannya. Imam ad-Dhahabī (w. 1348), misalnya, menuntut ilmu hingga usia 20 tahun dengan biaya orangtuanya. Namun umumnya, pemerintah mengalokasikan dana khusus untuk para penuntut ilmu. Di universitas dan sekolah-sekolah tinggi seperti Nizamiyyah, Aziziyyah, Mustansiriyyah dan sebagainya, baik staf pengajar maupun pelajar dijamin kehidupannya oleh badan wakaf masing-masing, sehingga bisa konsentrasi penuh pada bidang dan karirnya serta produktif menghasilkan karya-karya ilmiah. Dengan kemakmuran jugalah kaum Muslim dahulu dapat membangun istana-istana yang megah, perpustakaan-perpustakaan besar dan sejumlah rumah sakit.
Faktor keempat yang tak kalah pentingnya adalah dukungan dan perlindungan penguasa saat itu. Para saintis semisal Ibn Sina, Ibn Tufayl dan at-Tusi berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mengikuti patron-nya. Mereka menjadi penasehat sultan, dokter istana, atau sekaligus pejabat (Ibn Sina diangkat sebagai menteri oleh penguasa Hamadan waktu itu). Pentingnya patronase ini dibenarkan oleh sejarawan Toby Huff (1993): The considerable freedom and resources that certain outstanding philosophers and mathematicians had to pursue their studies, however, was always contingent upon the official protection of local rulers.
Kemunduran Sains di Dunia Islam
Lantas mengapa perjalanan sains di dunia Islam seolah-olah mendadak berhenti, mengapa cahaya kegemilangan itu kemudian redup lalu seolah lenyap sama sekali? Menjawab pertanyaan ini tidaklah sesederhana melontarkannya. Secara umum, faktor-faktor penyebab kematian sains di dunia Islam dapat dikelompokkan menjadi dua, internal dan eksternal.
Menurut Profesor Sabra (Harvard) dan David King (Frankfurt), kemunduran itu dikarenakan pada masa terkemudian kegiatan saintifik lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan praktis agama. Arithmetika dipelajari karena penting untuk menghitung pembagian harta warisan. Astronomi dan geometri (atau lebih tepatnya trigonometri) diajarkan terutama untuk membantu para muwaqqit menentukan arah kiblat dan menetapkan jadwal shalat. Penjelasan semacam ini tidak terlalu tepat, sebab asas manfaat ini acapkali justru berperan sebaliknya, menjadi faktor pemicu perkembangan dan kemajuan sains.
Jawaban lain menyatakan bahwa oposisi kaum konservatif, krisis ekonomi dan politik, serta keterasingan dan keterpinggiran sebagai tiga faktor utama penyebab kematian sains di dunia Islam. Ini pendapat David Lindberg (1992). Menurutnya, sains dan saintis pada masa itu seringkali ditentang dan disudutkan. Ia menunjuk kasus pembakaran buku-buku sains dan filsafat yang terjadi antara lain di Cordoba. Tak dapat dipungkiri bahwa krisis ekonomi dan kekacauan politik amat berpengaruh terhadap perkembangan sains. Konflik berkepanjangan disertai perang saudara telah mengakibatkan disintegrasi, krisis militer dan hancurnya ekonomi. Padahal, kata Lindberg, a flourishing scientific enterprise requires peace, prosperity, and patronage. Tiga pilar ini mulai absen di dunia Islam menjelang abad ke-13 Masehi. Semua ini diperparah dengan datangnya serangan tentara Salib, pembantaian riconquista di Spanyol, dan invasi Mongol yang meluluh-lantakkan Baghdad pada 1258. Tidak sedikit perpustakaan dan berbagai fasilitas riset dan pendidikan porak-poranda. Ekonomi pun lumpuh dan, sebagai akibatnya, sains berjalan tertatih-tatih.
Faktor ketiga yang ditunjuk Lindberg biasa disebut ‘marginality thesis’. Sains di dunia Islam tidak bisa maju karena konon selalu dipinggirkan atau dianak-tirikan. Akibatnya, sains tidak pernah secara resmi diakui sebagai salah satu mata pelajaran atau bidang studi tersendiri. Pengajaran sains hanya bisa dilakukan dengan cara ‘nebeng’ atau diselipkan bersama subjek lainnya. Seberapa jauh kebenaran tesis ini masih terbuka untuk diperdebatkan. Pada level yang lebih tinggi, hal ini berimplikasi pada riset dan pengembangan. Konon para saintis saat itu banyak yang bekerja sendiri-sendiri, di laboratorium milik pribadi, meskipun disponsori dan dilindungi oleh patronnya. Namun demikian tidak ada lembaga khusus yang menampung mereka. Kesimpulan semacam ini agak problematik. Pertama, karena mencerminkan generalisasi yang tergesa-gesa dan, kedua, karena institutionalisasi tidak selalu berdampak positif tetapi bisa juga berakibat sebaliknya.
Selain itu, beberapa faktor internal seperti kelemahan metodologi, kurangnya matematisasi, langkanya imajinasi teoritis, dan jarangnya eksperimentasi, juga dianggap sebagai penyebab stagnasi sains di dunia Islam. Pendapat ini disanggah oleh Toby Huff. Menurutnya, mengapa di dunia Islam yang terjadi justru kejumudan dan bukan revolusi sains lebih disebabkan oleh masalah sosial budaya ketimbang oleh hal-hal tersebut diatas. Buktinya, Copernicus pun didapati menggunakan model dan instrumen yang didesain oleh at-Tusi. Tradisi saintifik Islam, tegas Huff, juga terbukti cukup kaya dengan pelbagai teknik eksperimen dalam bidang astronomi, optik maupun kedokteran. Oleh karena itu Huff lebih cenderung menyalahkan iklim sosial-kultural-politik saat itu yang dianggapnya gagal menumbuhkan semangat universalisme dan otonomi kelembagaan di satu sisi, dan membiarkan partikularisme serta elitisme tumbuh berkembang-biak. Di sisi lain, Huff menilai tidak terdapatnya skeptisisme yang terorganisir dan dedikasi murni turut mempengaruhi perkembangan sains di dunia Islam.
Ada juga klaim yang menghubungkan kemunduran sains dengan sufisme. Memang benar, seiring dengan kemajuan peradaban Islam saat itu, muncul berbagai gerakan moral spiritual yang dipelopori oleh kaum sufi. Intinya adalah penyucian jiwa dan pembinaan diri secara lebih intensif dan terencana. Pada perkembangannya, gerakan-gerakan tersebut kemudian mengkristal jadi tarekat-tarekat dengan pengikut yang kebanyakannya orang awam. Popularisasi tasawuf inilah yang bertanggung-jawab melahirkan sufi-sufi palsu (pseudo-sufis) dan menumbuhkan sikap irrasional dikalangan masyarakat. Tidak sedikit dari mereka yang lebih tertarik pada aspek-aspek mistik supernatural seperti keramat, kesaktian, dan sebagainya ketimbang pada aspek ritual dan moralnya. Obsesi untuk memperoleh kesaktian dan kegandrungan pada hal-hal tersebut pada gilirannya menyuburkan berbagai bentuk bid’ah, takhayyul dan khurafat. Akibatnya yang berkembang bukan sains, tetapi ilmu sihir, pedukunan dan aneka pseudo-sains seperti astrologi, primbon, dan perjimatan. Jadi lebih tepat jika dikatakan bahwa kemunduran sains disebabkan oleh praktek-praktek semacam ini, dan bukan oleh ajaran tasawuf.
Penutup
Memasuki era modern, sikap kaum Muslim terhadap sains terpecah menjadi tiga. Ada yang anti dan menolak mentah-mentah, ada yang menelan bulat-bulat tanpa curiga sedikitpun, dan ada yang menerima dengan penuh kewaspadaan. Sikap yang pertama maupun yang kedua kurang tepat karena sama-sama ekstrim. Sikap yang paling bijak adalah bersikap adil, pandai menghargai sesuatu dan meletakkannya pada tempatnya. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kemajuan ataupun kemunduran sains dipengaruhi oleh dan tergantung pada banyak faktor internal maupun eksternal. Sebagai sebuah aktivitas kongkret, scientific enterprise mencerminkan nilai-nilai (epistemologis) yang dianut dan diamalkan para pelakunya. Kaum Muslim dapat meraih kembali kejayaannya jika mereka mau belajar dari sejarah agar tidak terjatuh ke jurang kegelapan berkali-kali.
Memasuki era modern, sikap kaum Muslim terhadap sains terpecah menjadi tiga. Ada yang anti dan menolak mentah-mentah, ada yang menelan bulat-bulat tanpa curiga sedikitpun, dan ada yang menerima dengan penuh kewaspadaan. Sikap yang pertama maupun yang kedua kurang tepat karena sama-sama ekstrim. Sikap yang paling bijak adalah bersikap adil, pandai menghargai sesuatu dan meletakkannya pada tempatnya. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kemajuan ataupun kemunduran sains dipengaruhi oleh dan tergantung pada banyak faktor internal maupun eksternal. Sebagai sebuah aktivitas kongkret, scientific enterprise mencerminkan nilai-nilai (epistemologis) yang dianut dan diamalkan para pelakunya. Kaum Muslim dapat meraih kembali kejayaannya jika mereka mau belajar dari sejarah agar tidak terjatuh ke jurang kegelapan berkali-kali.
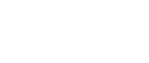





Problem hubungan agama dengan ilmu.
Sebelum kita berbicara secara panjang lebar seputar hubungan antara agama dengan ilmu dengan segala problematika yang bersifat kompleks yang ada didalamnya maka untuk mempermudah mengurai benang kusut yang terjadi seputar problematika hubungan antara agama dengan ilmu maka kita harus mengenal terlebih dahulu dua definisi pengertian ‘ilmu’ yang jauh berbeda satu sama lain,yaitu definisi pengertian ‘ilmu’ versi sudut pandang Tuhan dan versi sudut pandang manusia yang lahir melalui kacamata sudut pandang materialist.
Pertama adalah definisi pengertian ‘ilmu’ versi sudut pandang materialistik yang kita kenal sebagai ‘saintisme’ yang membuat definisi pengertian ‘ilmu’ sebagai berikut : ‘ilmu adalah segala suatu yang sebatas wilayah pengalaman dunia indera’,(sehingga bila mengikuti definisi saintisme maka otomatis segala suatu yang bersifat abstrak - gaib yang berada diluar wilayah pengalaman dunia indera menjadi tidak bisa dimasukan sebagai wilayah ilmu).faham ini berpandangan atau beranggapan bahwa ilmu adalah ‘ciptaan’ manusia sehingga batas dan wilayah jelajahnya harus dibingkai atau ditentukan oleh manusia.
Kedua adalah definisi pengertian ‘ilmu’ versi sudut pandang Tuhan yang mengkonsepsikan ‘ilmu’ sebagai suatu yang harus bisa mendeskripsikan keseluruhan realitas baik yang abstrak maupun yang konkrit sehingga dua dimensi yang berbeda itu bisa difahami secara menyatu padu sebagai sebuah kesatuan system.pandangan Ilahiah ini menyatakan bahwa ilmu adalah suatu yang berasal dari Tuhan sehingga batas dan wilayah jelajahnya ditentukan oleh Tuhan dan tidak bisa dibatasi oleh manusia,artinya bila kita melihatnya dengan kacamata sudut pandang Tuhan dalam persoalan cara melihat dan memahami ‘ilmu’ manusia harus mengikuti pandangan Tuhan.
Bila kita merunut asal muasal perbedaan yang tajam antara konsep ilmu versi saintisme dengan konsep ilmu versi Tuhan sebenarnya mudah : kekeliruan konsep ‘ilmu’ versi saintisme sebenarnya berawal dari pemahaman yang salah atau yang ‘bermata satu’ terhadap realitas,menurut sudut pandang materialist ‘realitas’ adalah segala suatu yang bisa ditangkap oleh pengalaman dunia indera,sedang konsep ‘realitas’ versi Tuhan : ‘realitas’ adalah segala suatu yang diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi ‘ada’,dimana seluruh realitas yang tercipta itu terdiri dari dua dimensi : yang abstrak dan yang konkrit,analoginya sama dengan realitas manusia yang terdiri dari jiwa dan raga atau realitas komputer yang terdiri dari software dan hard ware.
Berangkat dari pemahaman terhadap realitas yang bersifat materialistik seperti itulah kaum materialist membuat definisi konsep ilmu sebagai berikut : ‘ilmu adalah segala suatu yang sebatas wilayah pengalaman dunia indera’ dan metodologi ilmu dibatasi sebatas sesuatu yang bisa dibuktikan secara empirik.
Ini adalah konsep yang bertentangan dengan konsep dan metodologi ilmu versi Tuhan,karena realitas terdiri dari dua dimensi antara yang konkrit dan yang abstrak maka dalam pandangan Tuhan (yang menjadi konsep agama) konsep ‘ilmu’ tidak bisa dibatasi sebatas wilayah pengalaman dunia indera dan metodologinya pun tidak bisa dibatasi oleh keharusan untuk selalu terbukti langsung secara empirik oleh mata telanjang,sebab dibalik realitas konkrit ada realitas abstrak yang metodologi untuk memahaminya pasti berbeda dengan metodologi untuk memahami ilmu material (sains),dan kedua : manusia bukan saja diberi indera untuk menangkap realitas yang bersifat konkrit tapi juga diberi akal dan hati yang memiliki ‘mata’ dan pengertian untuk menangkap dan memahami realitas atau hal hal yang bersifat abstrak.dimana akal bila digunakan secara maksimal (tanpa dibatasi oleh prinsip materialistik) akan bisa menangkap konstruksi realitas yang bersifat menyeluruh (konstruksi yang menyatu padukan yang abstrak dan yang konkrit),dan hati berfungsi untuk menangkap essensi dari segala suatu yang ada dalam realitas ke satu titik pengertian.